Apakah Konsep Circular Fashion Cocok Diterapkan Di Indonesia?
Menurut data global, sampah yang ditinggalkan oleh industri fesyen mencapai 57 juta ton per tahun (Fashion Revolution, 2020). Sebagian besar dari sampah tersebut tidak dapat terurai karena pengunaan bahan bakunya tidak ramah lingkungan. Perkembangan yang begitu signifikan pada industri fast fashion meningkatkan kekhawatiran akan keberadaan sampah tekstil yang merusak bumi yang makin tak terkendali.

Industri tekstil dan fashion
disinyalir menyumbang 10% emisi gas rumah kaca secara global. Angka ini lebih
besar dari emisi gabungan seluruh penerbangan internasional dan pelayaran
internasional. Sebuah penelitian di
Eropa tahun 2017 juga menyebutkan bahwa konsumsi tekstil menghasilkan emisi sebanyak
654 kg CO2 per orang.
Industri tekstil pun diduga menjadi
penyumbang besar dalam pencemaran laut. Diperkirakan ada setengah juta ton
microfiber masuk dan mencemari lautan setiap tahunnya. Ini setara dengan 35% dari total
microplastics yang mencemari lingkungan.
Apa itu Circular Fashion?
Circular fashion dapat didefinisikan
sebagai sistem regeneratif di mana pakaian terus diedarkan selama nilai maksimumnya
dipertahankan. Setelah itu, pakaian dikembalikan ke lingkungan ketika tidak
lagi digunakan. Hadirnya konsep circular fashion sebagai respon dan
kekhawatiran atas semakin rusaknya kondisi lingkungan akibat produksi tekstil
dan garment berskala besar.
Namun, konsep tersebut tidak selalu mendapat tempat, terutama dalam kelompok industriawan produsen tekstil. Dimana beberapa pihak menilai praktek circular fashion berpotensi menghambat pertumbuhan industri tekstil. Dengan profit margin yang terbatas, industri tekstil masih mengandalkan volume besar guna memacu pertumbuhannya. Hal ini pun berdampak pada perkembangan industri fesyen yang makin cepat, selera konsumen yang terus serta kondisi ideal bagi tumbuh kembangnya industri tekstil.
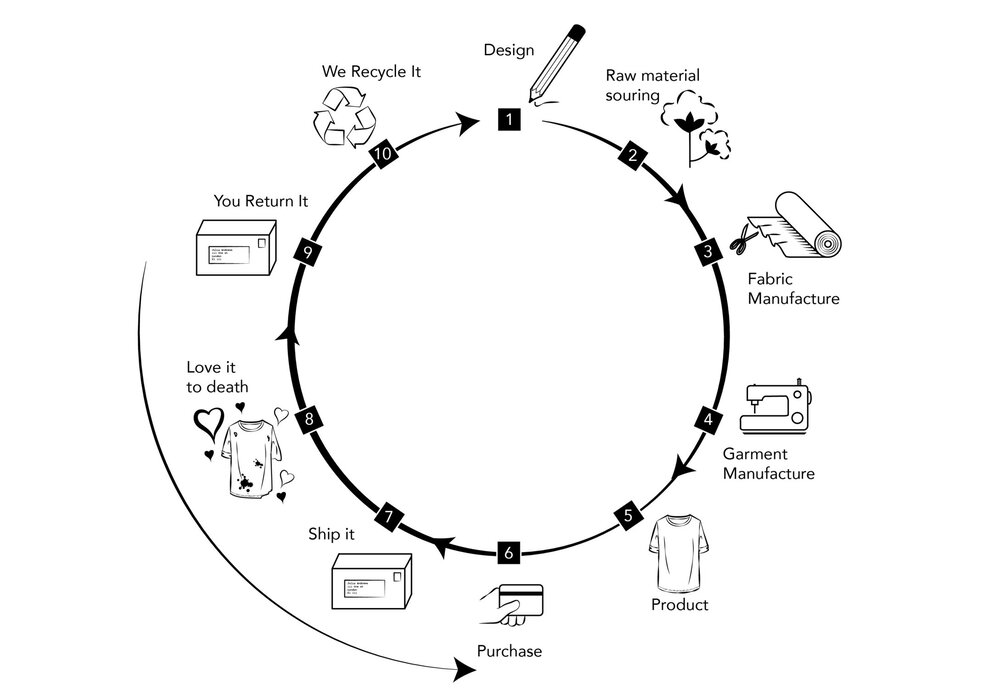
Kampanye slow fashion mendukung
pemakaian sandang lebih lama dan circular fashion menawarkan gagasan upcycling,
secara tidak langsung menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri tekstil
yang mempekerjakan jutaan tenaga kerja. Disamping itu, jasa penyewaanan pakaian
(clothing rental), penjualan pakaian bekas pakai (thrifting),
reparasi pakaian rusak, dan usaha sejenisnya juga berpotensi menghambat pertumbuhan
industri tekstil.
Pemerintahan negara berkembang yang
menjadikan industri tekstil sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi pasti
akan lebih protektif terhadap pertumbuhan industri dalam negeri mereka. Secara
represif pemerintah melarang impor pakaian bekas pakai dan usaha penjualan
pakaian bekas dianggap sebagai bisnis illegal. Tujuan utamanya tentu saja untuk
mempertahankan jumlah permintaan masyarakat terhadap pakaian dan sebagai
perlindungan konsumen dari penyebaran penyakit menular.
Apakah Konsep circular fashion cocok diterapkan di Indonesia?
Indonesia dengan penduduk lebih
dari 270 juta jiwa merupakan salah satu negara yang masih menempatkan industri
tekstil sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.
Bagi Indonesia, industri teksil adalah bidang yang diharapkan mampu
memenuhi kebutuhan sandang nasional, penyumbang devisa negara sekaligus penyedia
lapangan pekerjaan secara masif.
Lalu, apakah konsep circular fashion tidak cocok diterapkan di Indonesia? Padahal dari sudut pandang kelestarian lingkungan, industri tekstil dan garmen di Indonesia menyumbang lebih dari 1 juta ton sampah pakaian bekas pakai per tahun dan 500 ribu ton sampah tekstil lain berupa sisa potongan kain, benang dan sejenisnya dari industri tekstil dan garment.

Melihat perkembangan jumlah
penduduk dan keterbatasan sumber daya, model bisnis linier memang kurang sesuai
untuk dipertahankan. Sementara konsep
bisnis sirkular perlu benar-benar mendapat perhatian. Selain itu, adaptasi
terhadap konsep bisnis sirkular tetap dibutuhkan.
Re-orientasi tujuan bagi negara
yang masih mengandalkan industri tekstil sebagai penopang pertumbuhan
ekonominya nampaknya perlu dijadikan bahan pertimbangan. Khusus untuk
negara-negara tersebut praktek circular fashion dapat dilekukan melalui
pendaurulangan busana, mengubah pakaian bekas pakai menjadi bahan baku tekstil berkualitas
atau setara dengan bahan baku aslinya.
Di Indonesia sendiri, praktek daur ulang kain menjadi serat tekstil mulai diterapkan oleh beberapa pabrik. Tetapi proses ini masih dilakukan secara mekanis, sehingga kualitas seratnya cenderung lebih rendah dibanding serat asli. Sehingga penggunaan produk hasil daur ulang ini hanya terbatas pada kebutuhan tekstil non fesyen atau fesyen dengan konsep artisan.

Tampaknya Indonesia membutuhkan
lebih banyak industri daur ulang tekstil, baik daur ulang mekanis maupun daur
ulang kimia yang mampu menghasilkan kualitas bahan yang setara produk
virgin. Karena tujuan utama dari konsep circular
fashion adalah untuk memastikan bahwa pakaian tersebut berasal dari bahan
baku yang aman dan dapat diperbaharui (renewable).
“We can’t choose between the
(economic) growth and the sustainability – we must have both”, ungkap Paul
Polman (Wakil Ketua UNFCC). Kita tidak
selayaknya mempertentangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan
karena keduanya harus berjalan beriringan.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga tidak harus dengan membahayakan
kelestarian lingkungan. Demikian pula
sebaliknya usaha-usaha pelestarian lingkungan tidak perlu dengan menghambat
pertumbuhan ekonomi.
Sumber: Buletin Tekstil Edisi 19
Search
Categories
Recent Posts
-
 Sepatu Mary Jane dan Pesonanya yang Tak Pernah Usang
Sepatu Mary Jane dan Pesonanya yang Tak Pernah Usang
-
 Tips Memilih Handuk Wajah Untuk Kulit yang Sehat
Tips Memilih Handuk Wajah Untuk Kulit yang Sehat
-
 Cerdik! Ini 7 Strategi Rahasia Aerostreet Dalam Membangun Brandnya
Cerdik! Ini 7 Strategi Rahasia Aerostreet Dalam Membangun Brandnya
-
 Outfit Check ala Gen Z, Gaya Fashion Stylish yang Lebih Berkelanjutan
Outfit Check ala Gen Z, Gaya Fashion Stylish yang Lebih Berkelanjutan
-
 Jam Tangan Kesayanganmu Berembun? Coba Atasi Dengan Cara Ini!
Jam Tangan Kesayanganmu Berembun? Coba Atasi Dengan Cara Ini!
-
 Teknik Sunprint (Cyanotype), Cara Mencetak Motif Daun di Kain dengan Sinar Matahari
Teknik Sunprint (Cyanotype), Cara Mencetak Motif Daun di Kain dengan Sinar Matahari
-
 Mengenal Dunia Debutante: Lebih dari Sekadar Pesta, Ini Adalah Kiblat Fashion "Old Money"
Mengenal Dunia Debutante: Lebih dari Sekadar Pesta, Ini Adalah Kiblat Fashion "Old Money"
-
 Apa Itu Mesin Jahit Heavy Duty? Cek Fitur-fiturnya, Yuk!
Apa Itu Mesin Jahit Heavy Duty? Cek Fitur-fiturnya, Yuk!
-
 Teknik Intrecciato, Cerita di Balik Tren Tas Motif Anyaman yang Mempesona
Teknik Intrecciato, Cerita di Balik Tren Tas Motif Anyaman yang Mempesona
-
 Malioboro Mall, Sejarah Toserba Modern Pertama di Yogyakarta
Malioboro Mall, Sejarah Toserba Modern Pertama di Yogyakarta
-
 Sepatu Mary Jane dan Pesonanya yang Tak Pernah Usang
Sepatu Mary Jane dan Pesonanya yang Tak Pernah Usang -
 Tips Memilih Handuk Wajah Untuk Kulit yang Sehat
Tips Memilih Handuk Wajah Untuk Kulit yang Sehat -
 Cerdik! Ini 7 Strategi Rahasia Aerostreet Dalam Membangun Brandnya
Cerdik! Ini 7 Strategi Rahasia Aerostreet Dalam Membangun Brandnya -
 Outfit Check ala Gen Z, Gaya Fashion Stylish yang Lebih Berkelanjutan
Outfit Check ala Gen Z, Gaya Fashion Stylish yang Lebih Berkelanjutan -
 Jam Tangan Kesayanganmu Berembun? Coba Atasi Dengan Cara Ini!
Jam Tangan Kesayanganmu Berembun? Coba Atasi Dengan Cara Ini! -
 Teknik Sunprint (Cyanotype), Cara Mencetak Motif Daun di Kain dengan Sinar Matahari
Teknik Sunprint (Cyanotype), Cara Mencetak Motif Daun di Kain dengan Sinar Matahari -
 Mengenal Dunia Debutante: Lebih dari Sekadar Pesta, Ini Adalah Kiblat Fashion "Old Money"
Mengenal Dunia Debutante: Lebih dari Sekadar Pesta, Ini Adalah Kiblat Fashion "Old Money" -
 Apa Itu Mesin Jahit Heavy Duty? Cek Fitur-fiturnya, Yuk!
Apa Itu Mesin Jahit Heavy Duty? Cek Fitur-fiturnya, Yuk! -
 Teknik Intrecciato, Cerita di Balik Tren Tas Motif Anyaman yang Mempesona
Teknik Intrecciato, Cerita di Balik Tren Tas Motif Anyaman yang Mempesona -
 Malioboro Mall, Sejarah Toserba Modern Pertama di Yogyakarta
Malioboro Mall, Sejarah Toserba Modern Pertama di Yogyakarta
KAIN POPULER
ARTIKEL POPULER







